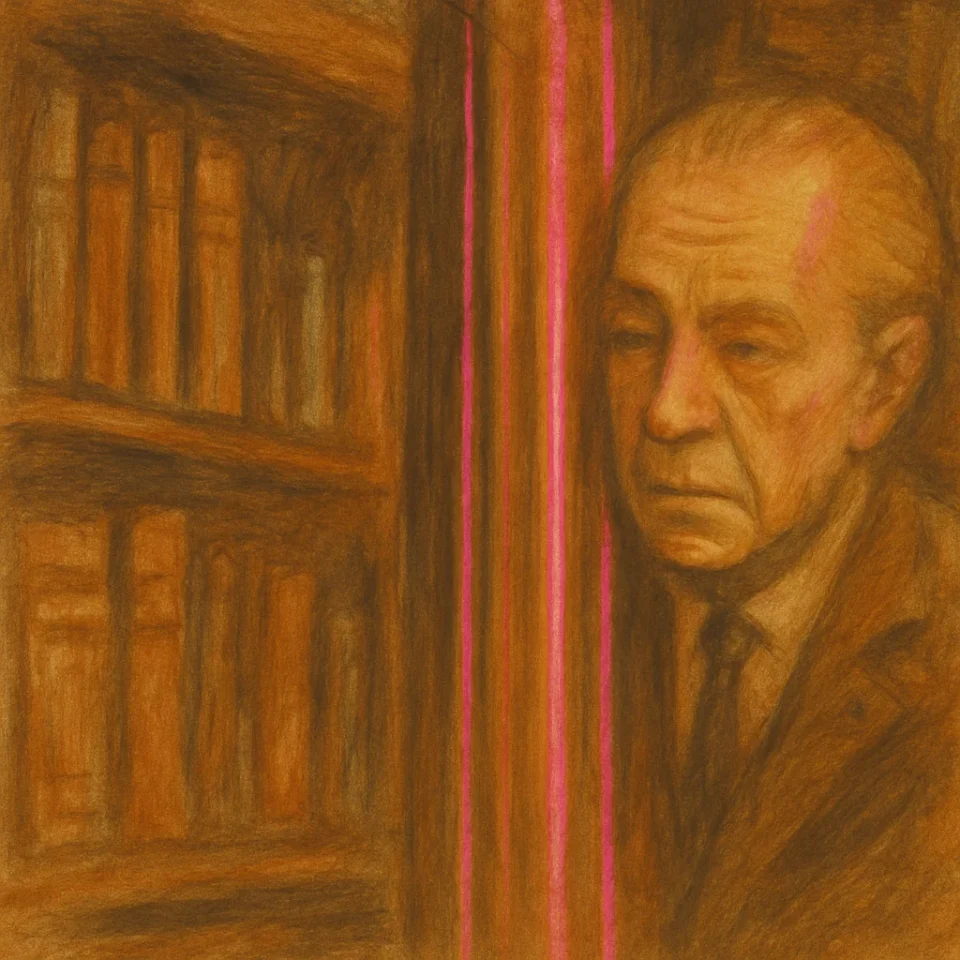Di suatu wilayah yang tak tercatat dalam peta sastra, tempat di mana para penulis bermain dengan reruntuhan teks, fanfic bukan sekadar tiruan, melainkan pembangkitan. Dalam puisi aku menamainya Prosedur Pembunuhan Idola, karya fanfic ditampilkan melalui proses yang sama, penghancuran dan penghidupan kembali. Dalam prosa, fanfic juga bisa menjadi kritik dalam bentuk politically correct, bisa juga menjadi parodi. Cervantes, dengan Don Quijote, mengolok-olok roman ksatria abad pertengahan, tetapi tanpa disadari, dia justru melahirkan novel modern. Di sini, parodi menjadi senjata untuk membongkar sekaligus membangun kembali. Begitu pula fanfic: ia adalah parodi yang serius, sebuah upaya untuk membaca ulang dunia melalui retakan yang ditinggalkan pengarang asli.
Borges, dalam esai Kafka dan Para Pendahulunya, menulis bahwa setiap penulis menciptakan tradisi mereka sendiri. Fanfic, dalam konteks ini, adalah tradisi yang terbalik: ia meruntuhkan monumen teks induk, lalu membangun kuil baru dari puing-puingnya. Seperti labirin Borges, fanfic tidak memiliki pusat; ia adalah ruang tak berdimensi tempat setiap sudut pandang bisa menjadi jalan keluar atau jalan buntu.

The Great Gatsby karya F. Scott Fitzgerald (1925) adalah kisah tentang ilusi yang diabadikan melalui mata Nick, seorang pengamat yang terjebak dalam batas perspektifnya sendiri. Tapi bagaimana jika kita mencuri kunci dari rumah Gatsby yang megah dan membiarkan dindingnya berbicara? Rumah itu, dalam keheningannya, menyimpan lebih banyak kebenaran: ia melihat Daisy menangis di kamar mandi emas, mendengar suara pesta yang tak pernah sepi, dan merasakan debu yang menempel pada jas Gatsby yang tak pernah dipakai.
Dalam fragmen fiksi ini, rumah bukan sekadar latar—ia adalah saksi yang teralienasi, seperti benda-benda dalam The Metamorphosis karya Kafka yang menyaksikan Gregor Samsa tanpa bisa berteriak. Borges, dalam The House of Asterion, telah membuktikan bahwa sudut pandang seorang “monster” bisa mengubah labirin menjadi istana. Demikian pula, rumah Gatsby yang bisu adalah labirin yang menunggu untuk dijelajahi oleh imajinasi pembaca.

Ketika aku membayangkan Hamlet dari sudut pandang Ophelia, aku tidak ingin dia menjadi korban pasif. Ophelia versiku adalah seorang filsuf yang terperangkap dalam tubuh perempuan muda—dia mengamati kegilaan Hamlet dengan mata seorang antropolog. Di balik kata-kata puitisnya, dia merenungkan: Apakah kegilaan adalah bahasa yang hanya dipahami oleh mereka yang menolak bermain dalam sandiwara realitas?
Hamlet bukan lagi pahlawan tragis, melainkan minotaur yang menggerogoti labirin dirinya sendiri. Ophelia, seperti Ariadne, mencoba memintal benang makna dari kekacauan itu, akan tetapi benangnya putus, dan labirin itu akhirnya menelannya. Ini adalah ironi yang Borges sukai: upaya untuk memahami justru membawa kehancuran.

Dalam eksperimen Fragmen Benda—salah satu seri dalam buku baruku yang akan terbit—aku membiarkan kursi tua di kamar Gregor Samsa bercerita. Kursi itu ingat bagaimana Gregor dulu duduk sambil membaca koran—sebelum tubuh Gregor berubah jadi kecoa. Sekarang, kursi itu hanya menyimpan bayangan manusia yang hilang. Jendela yang tak pernah dibuka menggambarkan keterasingan ganda: Gregor terasing dari manusia, benda-benda terasing darinya.
Borges, dalam The Circular Ruins, menulis tentang mimpi yang melampaui pemimpi. Benda-benda Kafka adalah mimpi yang terjebak dalam realitas Gregor Samsa, namun mampu melampaui mimpi-mimpi Gregor yang paling liar sekalipun. Benda-benda ini adalah metafora untuk ketidakmampuan bahasa menjangkau esensi—seperti kata Borges, “Kita adalah sungai yang mengalir, tapi kita juga adalah sungai itu sendiri”.

Borges pernah menulis tentang seorang penulis yang menulis ulang Don Quixote kata demi kata dalam cerita Pierre Menard, Author of the Quixote. Hasilnya identik secara tekstual, tetapi maknanya berubah karena konteks zaman. Fanfic melakukan hal serupa dengan cara yang lebih vulgar: ia mencuri karakter, lalu memberinya jiwa baru. Ini adalah tindakan kurang ajar, tapi gak masalah, sebab seperti kata Borges, “Setiap penulis besar mencipta para pendahulunya”.
Contoh radikal adalah Wide Sargasso Sea karya Jean Rhys—fanfic Jane Eyre yang mengubah Bertha Mason dari “perempuan gila di loteng” menjadi korban kolonialisme. Di sini, fanfic bukan sekadar tambahan, melainkan koreksi sejarah. Ia membongkar hegemoni teks induk, seperti Borges membongkar ensiklopedia fiktif dalam Tlön, Uqbar, Orbis Tertius.

Metafora, bagi Borges, adalah jalan pintas menuju realitas yang lebih kompleks. Dalam The Aleph, sebuah titik kecil di ruang bawah tanah menyimpan seluruh semesta. Fanfic adalah Aleph versi sastra: ia memampatkan makna dari teks induk, lalu meledakkannya menjadi ribuan kemungkinan.
Misalnya, The Wind Done Gone (fanfic Gone with the Wind) menggunakan metafora “angin” untuk menggambarkan bagaimana narasi sejarah ditulis oleh para pemenang. Di sini, angin bukan sekadar fenomena alam, namun merupakan kekuatan yang menghapus suara budak dan perempuan. Borges tentu akan tersenyum melihat karya ini sebab baginya, metafora adalah persepsi seketika atas relasi objektif.

Roland Barthes menyatakan kematian pengarang. Bagi fanfic hal itu biasa saja sebab fanfic mampu membunuh pengarang dua kali: pertama, dengan merampas otoritas naratif; kedua, dengan menghidupkannya kembali sebagai hantu yang mengawasi setiap adaptasi. Borges, yang gemar bermain dengan pseudonim dan penulis fiktif, pasti setuju. Dalam Borges dan Aku, ia menulis: “Aku bertahan hidup, agar Borges bisa tetap hidup dan menulis”.
Fanfic adalah perwujudan dari paradoks ini: ia mengakui keabadian teks induk sambil membuktikan bahwa tak ada karya yang benar-benar final. Seperti labirin yang tak pernah selesai, fanfic adalah undangan untuk terus berjalan—bahkan jika jalan itu hanya ilusi. Dalam Dua Raja dan Dua Labirin, Borges menggambarkan labirin tak berujung ini sebagai sebuah padang pasir yang sangat luas.

Fanfic, dalam esensi Borgesian, bisa jadi sebuah upaya untuk menggali makna dengan menghancurkan makna. Ia seperti cermin di The Library of Babel yang memantulkan tak terhingga versi dari satu kalimat. Ketika kita menulis ulang Gatsby dari sudut pandang rumahnya, atau Hamlet dari sudut pandang Ophelia, kita tidak hanya mengubah cerita—kita menciptakan semesta paralel di mana setiap detil memiliki suara.
Borges pernah berkata: “Kita adalah ingatan kita… kita adalah museum yang kacau”. Fanfic adalah museum itu: ruang di mana setiap pengunjung boleh menyusun ulang pamerannya. Dan kadang, seperti Cervantes, kita menemukan bahwa parodi justru lebih abadi daripada aslinya.
Karya di bawah ini adalah sebuah contoh fanfic dalam esensi borgesian.
SAL NISKALA: PENULIS SITI NURBAYA
Sal Niskala, seorang tokoh yang diselimuti ketenangan filosofis dan kehampaan modernitas, adalah penulis yang tampaknya telah hilang dalam narasi besar kesusastraan Indonesia. Ia dikenal luas sebagai pengarang Layar Terkembang, sebuah novel yang oleh banyak pembaca dianggap menandai puncak idealisme sastra Indonesia pasca-kolonial. Namun, Sal Niskala bukan sekadar penulis novel one hit wonder. Ambisinya lebih besar, lebih radikal; dan tentu saja, lebih absurd.
Pada suatu hari yang terlupakan di antara banyaknya sore Bandung yang berkabut, Sal mengajukan misi yang menggelikan namun transendental kepada dirinya sendiri: ia bertekad untuk menulis ulang Siti Nurbaya. Namun, pernyataan ini bukanlah niat untuk membuat adaptasi, reinterpretasi, atau sekadar memperbarui kisah lama itu dalam wacana kontemporer. Tidak. Sal Niskala tidak ingin menulis tentang Siti Nurbaya—ia ingin menulis seperti Marah Rusli, dengan detail yang sempurna, seakan-akan dia ialah Marah Rusli, dan hasilnya adalah teks yang identik dengan Siti Nurbaya yang diterbitkan di tahun 1922.
Sal Niskala tidak berniat hanya menciptakan sebuah cetak ulang, tetapi ingin menghidupkan kembali proses penciptaan itu, menelusuri jejak psikologis, sejarah, dan budaya Marah Rusli, hingga pada titik ia mencapai sesuatu yang tak terhindarkan: hasil akhir yang sama. Ini bukanlah parodi intelektual, melainkan tantangan spiritual dan filosofis. Sal ingin menulis ulang Siti Nurbaya sebagai sebuah tindakan yang sepenuhnya bebas dari pengaruh waktu, sebagai gestur metafisik yang menolak pengaruh dari konteksnya sendiri di Bandung abad ke-21.
Banyak yang menganggap Sal Niskala gila, tetapi para sastrawan yang benar-benar memahami cita-cita anehnya diam-diam mengagumi usaha ini. Dalam pembelaannya, Sal pernah berkata, “Apakah perbedaan antara membaca Siti Nurbaya hari ini dengan menulisnya kembali, kata demi kata, sampai teks itu menjadi milikku secara rohani? Membaca pun adalah pengulangan. Menulis adalah kepemilikan.”
Dalam catatan harian yang tersebar setelah keputusannya untuk menghilang dari kehidupan publik, tercatat bahwa Sal tidak langsung terjun dalam proyek ini. Ia mempersiapkan dirinya selama bertahun-tahun. Ia terlebih dahulu mempelajari surat-surat pribadi Marah Rusli, buku-buku yang ia baca, bahkan udara Sumatera Barat yang barangkali dihirupnya saat menulis novel legendaris itu. Sal Niskala bahkan memutuskan untuk mempelajari Bahasa Minangkabau dengan mendalam, agar bisa menangkap nuansa linguistik yang barangkali bersembunyi di antara baris-baris Siti Nurbaya. Semua ini dilakukan demi satu tujuan mulia: menulis ulang, kata demi kata, huruf demi huruf, apa yang sudah pernah dituliskan, namun dengan kesadaran dan intensi yang sepenuhnya baru.
Akhirnya, setelah bertahun-tahun persiapan mental, fisik, dan intelektual, Sal memulai penulisannya. Pada malam pertama dia menulis paragraf pertama;
Kira-kira pukul satu siang, kelihatan dua orang anak muda, bernaung di bawah pohon ketapang yang rindang, di muka sekolah Belanda Pasar Ambacang di Padang, seolah-olah mereka hendak memperlindungkan dirinya dari panas yang memancar dari atas dan timbul dari tanah, bagaikan uap air yang mendidih. Seorang dari anak muda ini, ialah anak laki-laki, yang umurnya kira-kira 18 tahun. Pakaiannya baju jas tutup putih dan celana pendek hitam, yang berkancing di ujungnya. Sepatunya sepatu hitam tinggi, yang disambung ke atas dengan kaus sutera hitam pula dan diikatkan dengan ikatan kaus getah pada betisnya. Topinya topi rumput putih, yang biasa dipakai bangsa Belanda. Di tangan kirinya ada beberapa kitab dengan sebuah peta bumi dan dengan tangan kanannya dipegangnya sebuah belebas, yang dipukul-pukulkannya ke betisnya.
Semakin dalam ia menulis, semakin ia merasa bahwa teks itu, teks yang ia tulis ulang dengan intensi dan kesadaran mutlak, benar-benar berbeda dari Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Bukan karena ada satu pun kalimat yang berubah, tetapi karena konteks historis, psikologis, dan budaya yang kini melekat pada setiap kata.

Di kemudian hari, Profesor Yassin, seorang kurator tanpa wajah, bahkan benar-benar membandingkan secara bersisian kedua buku itu, Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai karya Marah Rusli dengan Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai karya Sal Niskala, meski identik dalam segala hal dengan Siti Nurbaya, namun Siti Nurbaya bukan lagi Siti Nurbaya. Misalnya pada paragraf pertama, Marah Rusli menulis;
Kira-kira pukul satu siang, kelihatan dua orang anak muda, bernaung di bawah pohon ketapang yang rindang, di muka sekolah Belanda Pasar Ambacang di Padang, seolah-olah mereka hendak memperlindungkan dirinya dari panas yang memancar dari atas dan timbul dari tanah, bagaikan uap air yang mendidih. Seorang dari anak muda ini, ialah anak laki-laki, yang umurnya kira-kira 18 tahun. Pakaiannya baju jas tutup putih dan celana pendek hitam, yang berkancing di ujungnya. Sepatunya sepatu hitam tinggi, yang disambung ke atas dengan kaus sutera hitam pula dan diikatkan dengan ikatan kaus getah pada betisnya. Topinya topi rumput putih, yang biasa dipakai bangsa Belanda. Di tangan kirinya ada beberapa kitab dengan sebuah peta bumi dan dengan tangan kanannya dipegangnya sebuah belebas, yang dipukul-pukulkannya ke betisnya.
Profesor Yassin memahami, bahwa teks yang ditulis ulang oleh Sal Niskala, meskipun identik, sama dalam bentuk, namun telah berubah dalam makna. Pantun yang dibuat Siti untuk Samsul; “Ke rimba orang Kinanti, bersuluh api batang pisang. Jika tercinta tahankan hati, kirimkan rindu di burung terbang.” —yang dalam novel asli membawa kesan romantis dan tragedi, dalam tangan Sal Niskala menjadi komentar ironis terhadap pembatasan sosial di zaman modern. Penulisan ulang ini, meskipun secara tekstual sempurna, menjadi cerminan dari zamannya sendiri, sebuah rekonstruksi yang bukan sekadar salinan.

Sal menyelesaikan karyanya berbulan-bulan kemudian, lalu membagikan draft-nya kepada beberapa sahabat sastranya untuk menjadi pembaca pertama. Tanggapan mereka beragam, tetapi kebanyakan mereka mengaku heran. “Ini Siti Nurbaya, namun entah mengapa terasa berbeda,” ujar Frino Barus, seorang aktivis sastra di Poros Sastra Muda Bandung. “Ini novel yang sama dengan yang pernah kubaca sewaktu sekolah,” ujar Zahrana Kumayl—seorang aktivis sastra di komunitas Forum Lingkar pena–dengan ragu.
Tentu saja itu adalah Siti Nurbaya. Namun, Siti Nurbaya yang kini telah melewati tangan Sal Niskala bukanlah Siti Nurbaya yang diterbitkan pada tahun 1922 oleh Marah Rusli. Ini adalah Siti Nurbaya dari tahun 2003, yang ditulis dengan penuh kesadaran modernitas, dipenuhi dengan kecemasan abad ke-21, dan dihantui oleh ketidakpastian zaman.
Sal Niskala, dalam renungannya yang terakhir, menulis dalam jurnalnya: “Setiap kata yang ditulis dalam teks baru ini bukanlah reproduksi dari Siti Nurbaya. Ini adalah jalinan dari pengalaman manusia yang tak terhindarkan; penulis bukanlah pencipta, tetapi perantara. Saya menulis ulang sesuatu yang telah ada, tetapi dengan tangan dan jiwa yang lain. Inilah takdir dari setiap karya sastra: untuk selalu terulang, tetapi tak pernah sepenuhnya sama.”