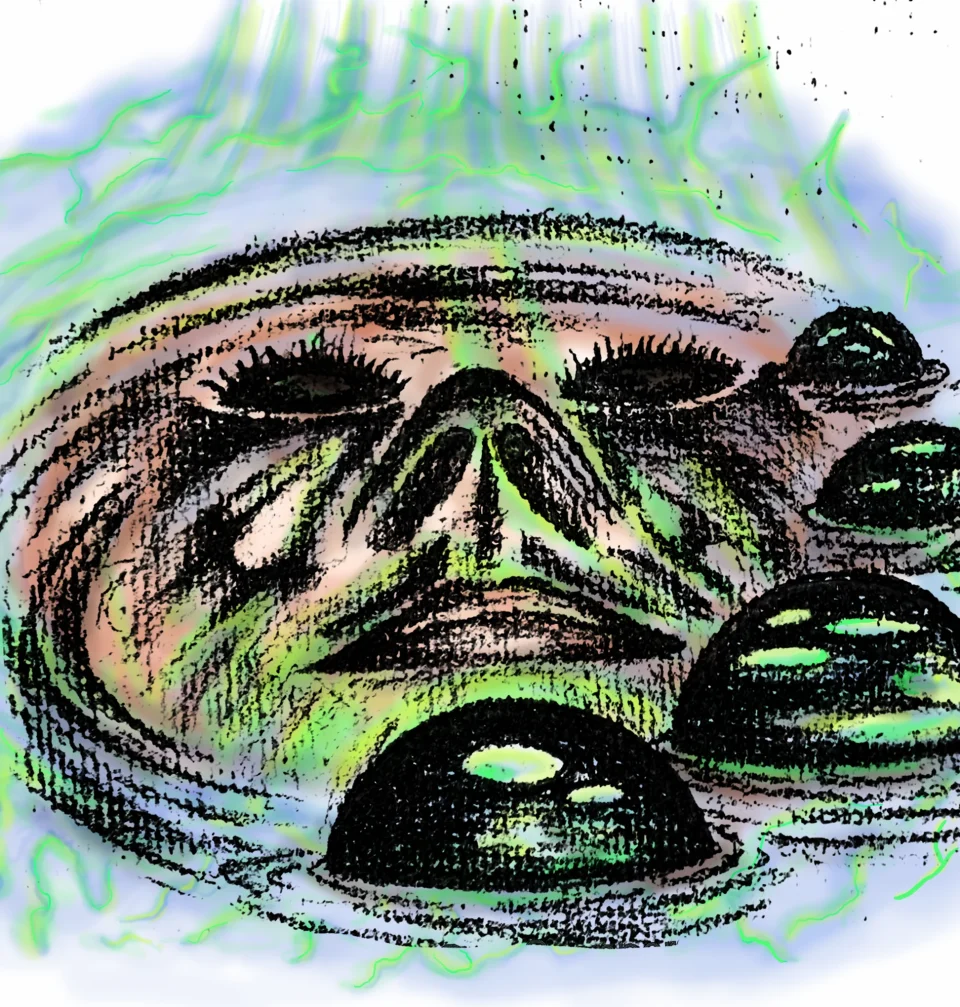Indeks Konten
Pengantar Penulis
Fragmen adalah teka-teki yang sengaja dibuat tak lengkap supaya pembaca ikut berdosa: menyusun, menebak, menambal. Dalam sastra eksperimental, fragmen berfungsi sebagai senjata dan obat—menyerang kebosanan narasi yang seragam, sekaligus menyembuhkan bahasa yang menolak satu makna tunggal. Fragmen—keras seperti pecahan kaca yang memantulkan cahaya acak tak terduga.
Aku melihat fragmen sebagai ruang kompromi antara ingatan dan lupa. Ia memotong waktu, estetika, dan suara. Di satu baris bisa ada gema pidato kuno; di baris lain, ada catatan kaki yang tak perlu. Tekniknya beragam: potongan prosa yang melompat logika, cut-up seperti tulisan di koran yang disobek lalu direkatkan ulang, catatan margin yang mengambil alih halaman, atau kalimat-kalimat yang berhenti di tengah napas; kepanjangan. Eksperimenku ini adalah pengujian: sampai sejauh mana pembaca mau ikut kerja keras membangun estetika?
Fragmen menuntut pembaca hadir sebagai produser makna. Peran pembaca berubah jadi tukang keramik yang merangkai pecahan menjadi vas baru; seringnya hasilnya tidak persis seperti aslinya, tetapi lebih jujur. Humor datang dari absurditas: tapi fragmen yang serius suka tiba-tiba menulis nota pembayaran di sebuah literer cafe.
Etika fragmen memecah narasi bisa menjadi bentuk perlawanan— menentang narasi besar yang menenggelamkan suara kecil. Tapi fragmen juga bisa terlena menjadi estetika elit yang menyombongkan ketidaklengkapannya. Tantangannya adalah menjaga fragmen tetap berisikan denyut kehidupan.
Fragmen adalah bentuk keberlanjutan yang tidak manis: ia mengakui keterbatasan kita—ingatan yang hilang, sejarah yang terpotong, kata-kata bernapas pendek—lalu mengundang kita untuk melanjutkan drama. Aku suka fragmen karena ia menuntut keberanian; suatu tekad tak gentar menghadapi gigitan realitas. Menulis fragmen berarti berani meninggalkan lubang, lalu menunggu seseorang masuk dan menyalakan lampu.
Fragmen-fragmen berikut ini kuambil dari serial buku berjudul Cermin Waktu yang terdiri dari lima buku (saat tulisan ini dimuat kelima buku ini belum diterbitkan), berisi kumpulan fragmen berdasarkan lima genre berbeda, setiap buku mewakili satu genre tertentu, berisi fragmen-fragmen eksperimental, yaitu Fragmen Benda, Fragmen Alam Ghaib, Fragmen Reinkarnasi, Fragmen Konspiratif, dan Fragmen Romantika. Aku hanya mengambil satu fragmen dari setiap buku untuk mewakilinya—sebagai teaser trailer.
Fragmen Benda: Pena Haus Darah (The 1998 Classic)
KATALOG LELANG UNTUK BENDA TERKUTUK NO. 178
LOT 001: PENA PARKER SONNET LIMITED EDITION (1998)
Deskripsi:
- Tinta hitam permanen, isi ulang khusus
- Badan perak berukir tulisan “A.V.C.”
- Mata pena 18k emas dengan retakan berbentuk komet
Provenance:
Diperoleh dari apartemen mewah dekat Monas di Jakarta Pusat. Mantan pemilik: Muhamad Suharno (pemimpin redaksi koran Pasukan Bersenjata, hilang 1998, sebulan setelah mendapat kiriman pena dari seseorang tidak dikenal, yang disusupkan ke mejanya melalui paket pos).
Catatan Kurator:
Benda ini menarik. Saat pertama kali ditemukan di laci besi terkunci, tinta di dalamnya masih mengalir. Kertas-kertas di sekitarnya menunjukkan tulisan yang sama berulang: “Buka surat yang pertama!”
 TRANSAKSI BIDDING
TRANSAKSI BIDDING
Bidder#789:
“Tawaran awal $10,000. Untuk koleksi artefak psikotropik.”
Bidder#333:
“$15,000. Saya mengenal Suharno. Dia gila setelah memakai pena ini untuk menulis tajuk rencana, sebuah propaganda untuk mengalihkan isu perekonomian yang amburadul.”
Bidder#001 (Anonim):
“$50,000. Tolong cek ujung pena. Ada serpihan kuku manusia di retakan komet.”
Kurator:
Lot ditunda. Pemeriksaan forensik mengonfirmasi: jaringan epitel di mata pena cocok dengan DNA Suharno.

LOT 002: PENA YANG SAMA (2003)
Deskripsi:
– Tinta berubah merah spontan saat menulis angka
– Badan menghitam seperti terbakar
– Bau tembakau dan kemenyan
Provenance:
Pemilik berikutnya adalah anak buah Suharno, redaktur pelaksana di medianya, Badarudin adalah seorang jurnalis teknologi, otaknya encer. Dikabarkan pena itu hilang di tangan Badarudin (ditemukan meninggal tahun 1999).
Dijual di pasar gelap Senen oleh dukun bernama Mbah Amin. Pemilik berikutnya: Walid Abdurrahim (Novelis, meninggal 2002, ditemukan pena di kerongkongannya).
Rekaman CCTV malam kematian Walid:
- 23:00: Pena bergerak sendiri menulis di papan tulis.
- 23:30: Tulisan berubah jadi semacam mantra dalam huruf yang aneh.
- 23:59: Tiba-tiba Walid menelan pena.
Catatan Kurator:
Dokumen yang ditemukan:
- Surat wasiat Walid bertuliskan “Buka surat yang pertama!”.
- Laporan investigasi proyek kotor yang tidak pernah terbit. Setiap halaman diisi coretan: “Buka surat yang pertama!”.
Foto Lampiran:
Close-up ujung pena. Pada perbesaran 1000x: wajah mikroskopis berteriak dalam tinta.

TRANSAKSI BIDDING
Bidder#567:
“$75,000. Saya ingin memakainya untuk menulis novel.”
Bidder#001:
“$100,000. Peringatan: Jangan pernah mengganti tinta. Bagian ‘A.V.C’ di badan pena adalah singkatan Anima Vincta Catenis (Jiwa yang Dirantai).”
Bidder#789:
“Tarik tawaran. Staf saya melaporkan demam 40°C setelah memegang foto lot ini.”

LOT 003: PENA YANG SAMA (2010)
Deskripsi:
- Tinta mengkristal membentuk huruf Jawa kuno
- Bisa menulis sendiri saat bulan purnama
- Menyebabkan halusinasi auditori: suara debat RUPS
Provenance:
Disita dari ruang baca Perpustakaan Nasional. Pemilik terakhir: Ega Wanti (Jurnalis, meninggal 2004,).
Catatan Kurator:
Tinta dalam pena tak pernah mengering.
Analisis Lab:
Kristal tinta mengandung darah manusia.

TRANSAKSI BIDDING
Bidder#001:
“$500,000. Saya tahu cara melepas kutukan: menuliskan semua nama korban dengan tinta ini di atas kulit sendiri.”
Bidder#999 (Baru):
“$1,000,000. Aku suka menulis cerpen.”
Peringatan: Bidder#999 harap baca laporan psikologis Lot 003. Pena ini pernah membuat anak 8 tahun menulis ulang kitab suci dalam huruf aramaik.
Kurator:
Pembeli terakhir tercatat secara resmi bernama Bambang Yudhi (cerpenis terkenal, ditemukan meninggal pada 2014)

LOT FINAL: PENA + 13 BOTOL TINTA MISTERIUS
Deskripsi:
- Setiap botol tinta berlabel nama para penulis yang hilang atau meninggal
- Botol tinta berlabel BIDDER #777 “Mulyadi” (wartawan bodrex, meninggal 2024, diserang penyakit kulit)
- Surat dari Suharno (1998): “Buka surat yang pertama. Tolong hapus semua.”
Catatan Kurator:
Kami tidak bertanggung jawab atas:
- Tulisan yang muncul di kulit pemilik
- Suara rapat direksi di malam hari
- Cairan hitam yang merembes dari buku-buku di atas rak
Peringatan Khusus:
Jangan pernah menuliskan nama Anda sendiri.

TRANSAKSI AKHIR
Bidder#008:
“$10,000,000. Ini untuk mengubur semua dosa keluarga.”
Bidder#666 (Baru):
“$66,600,000. Saya adalah Suharno. Pena itu milikku.”
Sistem:
ERROR. Bidding ditutup. Lot menghilang dari gudang. Ditemukan catatan di meja kurator: “TERIMA KASIH. KAMI TELAH BERTUMBUH.”

LAMPIRAN RAHASIA (Deklasifikasi 2077)
- Catatan dokter jiwa Bidder#777: Anaknya kini menulis di udara dengan jari. Tinta muncul dari pori-porinya.
- Spesimen tinta lot terakhir: Sel hidup yang bereproduksi dalam medium pena THE 1998 CLASSIC, Sang Pena Haus Darah.
Kode Genomik Tinta:
ATCG-666-AVC-HW-SL-… [terpotong]

Epilog:
Di kamar kebesaran Bidder #008 yang dihantui spirit Bidder #666, tengah malam, pena itu mulai menulis sendiri:
Bab 1: Revisi Sejarah
Tiap goresan adalah pengadilan.
Tiap titik adalah kuburan.
Dan kau… kau hanya tangan
Dengan sejarah yang lebih hitam
daripada tinta.
Aku bukan alat.
Aku arsip berjalan.

Fragmen Alam Ghaib: Tiga Hantu Famous di Negeri Kapitalis
KUNTILANAK
Setelah pergi dari Tangerang dan tidak lagi dagang es coklat, banyak yang tanya, “Sekarang kerja apa?”. Ok, kujawab di sini ya, jadi gak mesti balas pesan satu per satu, “Human trafficking.”
Jadi beberapa bulan terakhir ini aku dan seorang teman tiap malam berburu kuntilanak di rumah-rumah kosong dan kebun-kebun tak terurus. Biasanya ketemu 1 hingga 2 kunti dalam seminggu. Terus kami paku ubun-ubun mereka. Setelah jadi orang, lantas kami jual ke Arab untuk jadi pekerja migran. That’s what I do for the living, exploiting my imagination.
Buat teman-teman internasional, kuntilanak itu kira-kira secara tampilan mirip dengan Banshee—perempuan bergaun putih, bermuka pucat dan berambut panjang—bedanya Banshee suka menjerit, Kuntilanak suka tertawa histeris, bikin bulu kuduk berdiri. Kuntilanak memiliki kisah yang mirip dengan kisah La Lorona—suka menculik anak kecil, atau dalam kasus kuntilanak adalah bayi yang baru dilahirkan—Kuntilanak biasanya menyamar menjadi dukun beranak untuk mendapatkan buruannya.
Ada banyak kisah berbeda dan berkembang seputar Kuntilanak, dari cerita aslinya yang seorang penyihir penculik bayi dalam dongeng-dongeng Melayu kuno hingga bertransformasi menjadi hantu urban yang jika dipaku ubun-ubunnya maka mereka akan kembali menjadi manusia. Paku yang dipakai pun paku khusus yang sudah ditatahkan rajah doa tertentu pada permukaan pakunya. Kamu bisa beli paku ini di toko yang jual barang-barang mistik, di Jawa Barat biasanya suka ada di pasar-pasar, dari kemenyan, dupa, bukhur, jimat, hingga senjata pusaka ada di warung ini.
Nama kuntilanak sendiri dalam bahasa kunonya—Pontianak— malah dijadikan sebuah nama kota tempat kisah ini bermula. Kota Pontianak berada di Pulau Borneo, menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu kota terbesar di Borneo.
TUYUL
Selain berburu kunti dan menjualnya ke Arab, aku dan temanku juga sedang merintis budidaya ternak tuyul—manusia kecil seperti anak-anak, botak, dan suka mencuri. Sebenarnya mancing tuyul itu agak mudah, kita hanya bermodalkan ikan mas busuk lalu simpan di tempat yang kita ingin tuyul itu datang dan bersarang. Namun yang pelik adalah karena tuyul itu liar dan tidak suka diperintah, persis kayak kucing, kita gak ingin dia diternak dekat-dekat rumah kita—yang ada ntar duit kita yang kebobolan. Kita mesti cari lokasi yang tepat untuk sebar ikan mas busuk itu. Jangan di daerah kompleks perumahan kelas menengah atau di kampung kelas menengah ke bawah. Tentu kita gak ingin merampok dari mereka, kan?
Lokasi paling tepat adalah di sekitar perumahan elit, sasaran empuk dan nir rasa bersalah. Permasalahan utamanya adalah orang-orang super kaya sudah jarang menyimpan uang kas di dalam rumah. Tapi tak apa sebab untuk sebuah awal ini cukup lumayan. Setidaknya kita dapat bergepok-gepok uang kembalian. Dan anggap saja ini fase latihan bagi tuyul-tuyul itu. Minim risiko juga, bagi orang kaya kehilangan uang kembalian tentu bukan masalah.
Nah, setelah kita bisa mengumpulkan tuyul cukup banyak dan skill-nya mulai terasah, kita bisa mulai training mereka untuk upgrade skill sehingga bisa mengikuti orang-orang kaya itu pergi ke ATM, lalu menggasak uang mereka di sana.
Catatan:
Hingga saat ini tuyul belum bisa merampok uang dari ATM/Bank secara langsung karena sebuah perjanjian mengikat antara tuyul dan para pemilik bank. Ini adalah semacam perjanjian kuno yang dilakukan oleh para leluhur tuyul dan leluhur para pemilik bank pada sekitar tahun 500-an sebelum masehi di Eropa. Di zaman modern, para pemilik bank membangun program anti-tuyul di ATM-ATM, untuk mengantisipasi tuyul-tuyul nakal yang gak punya sopan santun.
Saat ini aku dan beberapa tuyul nakal sedang mengembangkan program anti-anti-tuyul.
GENDERUWO
Lain halnya dengan gandarwa atau genderuwo atau genderewo—makhluk besar seperti raksasa menyeramkan dipenuhi rambut panjang kasar di sekujur tubuhnya, kaum ini tidak bisa menguntungkan kita secara materi sebab semua hal yang mereka gasak akan dimakan sendiri, namun sangat cocok untuk melampiaskan dendam kesumat.
Genderewo bisa diundang dan ditanam di sebuah rumah yang kita inginkan. Kaum ini akan menggasak semua hal yang ada di dalam rumah itu hingga berakibat pemilik rumah jatuh miskin secara sangat terpuruk, usahanya bangkrut, di PHK, hingga rumah tangganya hancur, hancur sehancur-hancurnya.
Ingatlah bahwa genderewo sangat sulit untuk diusir, hampir tidak ada satu pun manusia, dukun paling sakti sekalipun, yang dengan gampang bisa mengusir genderewo jika sudah ditanam di suatu rumah. Dan jika pada akhirnya tidak ada lagi yang bisa dimakan di rumah itu, mereka akan berbalik pada orang yang menanamnya.
Cara mengundang dan menanam genderewo sangat mudah dan murah, namun karena risikonya tinggi, aku gak akan kasih tahu caranya di sini. Kecuali jika untuk digunakan menghancurkan sebuah keluarga koruptor yang jahat, aku bisa bocorkan caranya secara privat, DM aja.
Sebenarnya ada cara efektif mengusir genderewo jika tugasnya membalaskan dendam kita sudah sukses, tapi ya itu tadi, sangat rumit, berbiaya mahal, dan berisiko tinggi.
Jadi sebaiknya lupakanlah urusan genderewo ini. Selain memiliki risiko tinggi, pembalasan dendam tidak bisa memuaskan dahaga kita, sekeras dan sebanyak apapun kita melampiaskannya. Tulisan ini ada hanya sekedar info, bukan untuk dipraktekan.
Seperti rindu, dendam tidak perlu dibayar tuntas, redamlah dalam hati semaksimal mungkin. Memaafkan adalah jalan terbaik untuk orang-orang baik.

Fragmen Reinkarnasi: Senyum Dua Senti
“Ada tiga macam rahasia:
rahasianya rahasia,
rahasia ilahi,
dan rahasia diri sendiri.
Rahasia diri sendiri berada dalam cahaya;
sangat cerah, megah, tanpa kerudung apapun;
bening tanpa noda apapun;
meski demikian ia tak
kasat mata. “
– Tembang 111
“Kekasihku, di jalan ada perjumpaan dan sua kembali. Tetapi kita
berjalan sendiri-sendiri. Kubawa ragaku menempuh kemegahan Suluk,
dan kamulah tembang laras Suluk itu. Kau mengira aku pergi, padahal
aku mengembara dalam dirimu.”
– Tembang 113
Dari buku Centhini “Empat Puluh Malam dan Satunya Hujan“
oleh Elizabeth D. Inandiak,
Galang Press, Cetakan II, April 2005
Ini kisah tentang seekor lebah yang jatuh cinta pada ratunya. Begitu pun sebaliknya. Lalu mereka menjalin sebuah hubungan rahasia yang sangat diharamkan oleh koloni sebab hukum alam menyebutkan bahwa ratu harus membagi cintanya kepada seluruh lebah dalam koloni, alih-alih hanya mencintai seekor lebah saja. Tapi serapat apapun pintu rahasia ditutup, baunya tetap tercium. Salah satu dari dewan koloni mencium skandal ini.
Demikianlah, mereka berdua dihukum oleh dewan koloni, ratu tetap menjadi ratu, sebab ratu memiliki kekebalan khusus terhadap hukum yang menimpanya, sementara si lebah pekerja dihukum mati demi keadilan dan kelangsungan koloni.
Sejak saat itu Sang Ratu berubah menjadi gunung es, dingin-gelap-kering. Cintanya sudah mati seiring kematian kekasihnya. Setiap larva baru yang lahir dari rahimnya berkembang menjadi lebah-lebah ganas dan agresif yang mampu membunuh seekor gajah dalam sekali sengat. Hal ini membuat koloni menjadi hidup dalam ketegangan dan ketakutan.
Ekosistem berubah drastis, iklim ikut berubah, cuaca di seluruh dunia mengalami kekacauan layaknya letusan Tambora. Angin dingin sangat ekstrem datang dari selatan tempat Sang Ratu Lebah bersemayam; Laut Jawa membeku, Gunung Gede bersalju, Jakarta menggigil, jam dinding berhenti berdetak.
Lebah-lebah muda menyerbu kota bagai sebatalion uruk-hai yang siap meluluhlantakkan Helm’s Deep—pertahanan terakhir Bangsa Rohan.
Tiada satu anasir pun yang mampu mencegah serangan ini. Para lebah muda ini membunuh apa saja-siapa saja yang mereka lewati. Mutasi yang terjadi pada genetika mereka membuatnya menjadi sangat tangguh, 33 kali lebih kuat dari lebah biasa.
Penduduk kota punah, sebagian dihajar hypothermia, sebagian lagi disengat para lebah mutan. Lalu para lebah pun pada akhirnya menemui ajal satu per satu setelah kuota sengatan sudah habis.
Pada akhirnya hanya tinggal Sang Ratu yang masih bertahan hidup meski dengan kebekuan yang sudah melewati ambang batas.
Lalu bumi meledak, tidak tahan dengan perubahan yang begitu cepat ini. Sang Ratu tersenyum sinis pada babak terakhir ledakan bumi, pada sebuah adegan ketika segalanya hancur dan berubah menjadi cahaya.
Lalu hampa.
Sang Ratu melayang tanpa dimensi.
Sendiri.
Tunggal.
Kosong.
Lalu perlahan, Sang Ratu sembuh dari penyakit dendam yang sudah mengakar menjadi kanker ganas di jantungnya, diobati oleh waktu yang—seperti biasa—bisa menyembuhkan apa saja.
Setelah itu setangkai mawar putih muncul dari ketiadaan, memantul menjadi ribuan tangkai, dan berpelangi di cerminan mata majemuk Sang Ratu.
Senyum sinisnya lenyap. Senyum manisnya melebar perlahan, menjadi dua senti.
Mawar putih bergerak lembut terbuai angin yang datang dari hembusan napas hangat Sang Ratu. Segera saja Semesta kembali muncul dalam adegan slow motion, dengan mawar putih itu sebagai pusatnya.
Istana Lebah kembali terbentuk dari balik kabut. Megah dan berkilau keemasan.
Masih dalam adegan lambat, seekor lelaki melayang jatuh dari balik awan menuju taman bunga, menghantam rumput gajah tebal empuk yang menjadi lantai taman yang indah itu.
Kekasih Sang Ratu sudah pulang. Bangkit dari kematian. Menjelma lelaki muda yang senyumnya melengkapi setiap hirupan napas Sang Ratu.
Seorang lelaki yang memberinya secarik puisi di atas kertas lusuh dalam sebuah amplop coklat bertepi hati berhiaskan mawar di sudut kanannya.
Sang Ratu membuka lipatan kertas itu, membaca puisi di dalamnya dengan bisikan lembut, nyaris tak terdengar:
Saat jutaan tetes embun
Bergeser pada daun
Menyeruakkan riuh suara
Gesekan air menjadi gemuruh
Lalu kulihat tubuhmu meliukkan jutaan adrenalin
Pada mataku … Pada jantungku
Bersamamu…
Gravitasi mati
Mati tadi pagi
Saat ucapan awal hati
Setiap hari pagi
Menyapaku dengan alunan kinanti
Dan kopi pagi menjadi penanda
Lalu kudengar napasmu mengantarkan hujan badai feromon
Menembus waktu … Pada hidungku
Oh, Ratuku!
Gravitasi mati
Mati tadi pagi
Gravitasi mati di sini tadi pagi, Ratuku
Saat ucapan pembuka hati setiap pagi
Meluncur lagi dari seluruh permukaan inderamu
Menyapaku berkali-kali
Berbau hujan rintik dan angin barat
Rengekan anak-anak kucing dan kikik pelan
Menyegarkan napas menjadi puluhan kali lebih kuat
Puluhan kali lebih hidup dalam setiap senyumnya
Puluhan kali lebih buas dalam setiap geramnya
Puluhan kali lebih ambigu dalam setiap ritmanya
Puluhan kali lebih mesra dalam setiap inkarnasinya
Puluhan kali lebih terang dari segala titik paling gelap
Saat badai rindu bulan gelap caitra
Menyerbu dengan obor tenaga matahari
Pada benteng terakhir kesendirian genitku
Dengan jejeran pohon sempur yang menjadi fosil
Gravitasi mati di sini tadi pagi, Ratuku
Saat suaramu menggelinjangkan noktah terjauh kesadaranku
Mendering abadi pada frekuensi yang mudah terabaikan
Menjadi denging penyimpan pesan
selamat pagi selamat pagi selamat pagi…
Terus seperti itu
Memantrai kepalaku agar terus mengingat namamu
Dan kutatahkan di langit-langit benakku
Aku tak mau mati lama-lama
Aku mati tak akan lama

Fragmen Konspiratif: Rahasia Keabadian
Aku pernah berpikir bahwa setiap teka-teki memiliki jawabannya, tersembunyi di balik lapisan waktu dan misteri. Tetapi ketika berbicara tentang Nicolas Flamel, jawabannya tidak pernah sesederhana itu. Seperti rumus kimia yang tak terpecahkan, hidupnya adalah enigma yang berlapis-lapis, penuh dengan bayang-bayang alkimia dan rahasia-rahasia yang hanya dimengerti oleh beberapa orang. Bahkan sekarang, bertahun-tahun setelah dia menghilang dari sejarah, Flamel masih menjadi teka-teki yang belum terselesaikan.
Kisah ini dimulai dengan dua orang, Nicolas dan Perenelle Flamel, pasangan yang menjalani kehidupan yang begitu jauh dari kebanyakan manusia biasa. Di Paris abad ke-14, mereka terlihat seperti pasangan lanjut usia yang tenang. Namun, seperti halnya batu filsuf yang mereka cari, penampilan selalu menipu.
Nicolas adalah seorang juru tulis biasa, tetapi pikirannya luar biasa. Setiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaan untuk hari itu, dia duduk di ruangan kecil di rumahnya, merenung di hadapan buku-buku kuno yang penuh dengan simbol-simbol rahasia, huruf yang tak dapat dibaca oleh mata manusia biasa. Perenelle, istrinya, adalah seorang wanita cerdas, dan, meskipun usianya telah lanjut, dia memiliki daya hidup yang luar biasa. Wajahnya, yang tampaknya menua seperti manusia biasa, menyimpan rahasia yang tidak bisa diungkapkan hanya dari pandangan luar.
Malam itu, di balik dinding batu rumah kecil mereka di Rue de Montmorency, cahaya lilin memantul di sudut-sudut kamar mereka. Perenelle duduk di dekat perapian, tangan halusnya menggenggam buku kuno yang baru saja tiba dari Timur. Buku itu tidak seperti yang lain—halamannya diisi dengan sketsa-sketsa detail dan kode rahasia, huruf-huruf berliku yang mengingatkannya pada tulisan kuno Mesir, Yunani, dan sesuatu yang lebih tua lagi.
“Ini dia,” Perenelle berbisik, suaranya tenang namun penuh keyakinan. “Kita telah menemukannya.”
Nicolas mengangkat kepalanya dari buku catatan yang penuh rumus, tatapannya bertemu dengan istrinya. Dalam cahaya redup itu, mata mereka menyala. Seperti dua ilmuwan yang terobsesi dengan kebenaran di balik semesta, mereka tidak pernah meragukan apa yang mereka cari. Mereka tahu bahwa rahasia keabadian—batu filsuf yang mitosnya diakui sepanjang masa—bukan hanya soal memanjangkan umur. Tidak, itu adalah rahasia untuk memahami dunia ini secara keseluruhan. Hidup yang panjang tanpa pemahaman akan alam semesta hanyalah kutukan.
Namun di sinilah masalahnya. Setiap lembar rahasia, setiap ramuan yang mereka coba buat, membawa mereka lebih dekat pada pencerahan—tetapi tidak cukup. Ada sesuatu yang hilang. Sebuah potongan yang tak mereka pahami. Hingga malam itu.
Di halaman terakhir buku itu, tergoreslah sesuatu yang tak pernah mereka duga: satu kata yang bergetar di bawah jari mereka seperti sentuhan ilahi. Essentia, inti dari segala hal. Jiwa, kesadaran. Esensi kehidupan itu sendiri.
Nicolas berdiri, matanya berbinar dengan ketegangan dan rasa takut sekaligus. “Ini lebih dari yang kita pikirkan,” katanya, suaranya hampir gemetar. “Ini bukan tentang tubuh. Ini adalah jiwa.”
Perenelle tersenyum tipis. “Tentu saja. Keabadian bukanlah tentang menghindari kematian fisik. Ini tentang menaklukkan batasan kesadaran itu sendiri.”

Bertahun-tahun berlalu, dan rumor tentang pasangan Flamel mulai beredar. Mereka dikatakan telah menemukan rahasia hidup kekal, tetapi tidak ada yang tahu pasti. Beberapa mengatakan mereka hanya ilusi, sementara yang lain bersumpah bahwa mereka telah melihat Nicolas dan Perenelle berkeliaran di antara manusia biasa, dalam wujud yang lebih muda, lebih penuh vitalitas.
Mereka lenyap dari pandangan publik, menghilang tanpa jejak, seolah-olah angin malam Paris telah menghapus mereka dari sejarah. Namun petunjuk-petunjuk kecil tetap tertinggal—pada simbol-simbol alkimia yang diukir di bangunan tua, pada surat-surat rahasia yang terungkap di tangan-tangan yang berkuasa, dan pada cerita-cerita berbisik tentang pasangan yang tak pernah menua.
Yang tak diketahui orang adalah bahwa Nicolas dan Perenelle memang berhasil. Namun keberhasilan mereka datang dengan harga yang mahal. Mereka tidak lagi terikat oleh waktu, tetapi juga tidak lagi sepenuhnya hadir di dunia yang kita kenal. Di suatu tempat di antara dimensi, di batas antara kehidupan dan kematian, kesadaran mereka bersatu dengan sesuatu yang lebih besar
Fragmen Romantika: Pertemuan Dua Naga
Jam empat kurang tujuh sore di Ubud, setelah hujan yang sebentar tapi niat banget, aku masuk ke sebuah toko kecil yang—kalau kau percaya pada bahasa benda-benda—jelas bukan toko biasa. Papan di depan pintu bambu: “NISKALA MOON: TAROT & MAGIC SHOP — ENERGY CLEANSING — HERBS — NO REFUND, ONLY KARMA.” Aku langsung teringat Sal–sahabatku. Bau toko ini tidak wangi dalam arti spa Instagram; baunya seperti laci seorang penyihir: kulit kayu manis, jahe tua, tembakau kering, kapulaga, dan sedikit logam yang terasa di lidah, seperti darah.
“Masuk aja, sayang,” ada suara dari dalam, perempuan, Bahasa Inggris, aksennya Slavia.
Aku melangkah masuk.
Toko itu seperti rak otak yang lupa dibereskan selama satu dekade. Kristal kuarsa dari Brazil; batu giok kerikil; botol ramuan kecil dengan label tulisan tangan (“tidur damai”, “luka lama”, “tidak lagi sayang orang brengsek”); gulungan kain perca berisi akar entah apa; kartu tarot dari Marseille sampai Rider-Waite sampai dek indie cetak terbatas bersampul Dewi Sri pakai kacamata hitam. Di sudut paling belakang, ada rak pisau kecil, tongkat kayu, dan benda-benda yang akan membuat polisi menatap lama lalu menggaruk kepala karena tidak ada pasal yang cocok.
Lalu ada dia—seorang perempuan, umur tiga puluhan, bermata abu-abu kebiruan, rambut pirang, cantik—sedang menumbuk sesuatu di lesung batu.
“Sebentar ya, aku lagi ngeracik pereda trauma laki-laki,” katanya sambil tersenyum dan mengedip padaku.
Aku berhenti. Ikut tersenyum dan membatalkan untuk bertanya retoris bernada heran buatan, trauma laki-laki? Sebab dia menoleh, tertawa kecil dan menjawab pertanyaanku tanpa perlu kuutarakan. “Bukan buatmu tapi buat perempuan yang traumanya disebabkan laki-laki. Kecuali kamu punya trauma yang disebabkan perempuan, bahan dasarnya sama, hanya waktu pembuatannya yang beda. Untuk Trauma Perempuan, harus kubuat lewat tengah malam.”
Dia cantik dengan cara yang nggak rapi. Rambut pirangnya diikat asal pakai stik kayu yang di salah satu ujungnya menempel sebuah kristal putih menyerupai cahaya api pucat. Rambut dan kulitnya sudah kena matahari sepuluh tahun Bali, turun seperti rumput kering ke bahu coklatnya. Kulitnya tidak putih turis, tapi warna madu terbakar, lendutan antara kecoklatan yang terjadi karena hidup, bukan karena paket sunbathing. Mata biru abu-abu, tapi bukan biru dingin Eropa. Lebih seperti biru air di sungai pegunungan setelah hujan: masih ada abu lumpur, masih ada cerita. Kaosnya gombrang tipis, rok batik tipis selutut, kaki telanjang. Lengan kirinya penuh gelang manik. Lengan kanannya penuh noda kunyit dan arang. Di pergelangan kakinya ada gelang dari biji-bijian dan satu potongan kecil logam yang entah kenapa menggetarkan udara.
Aku berdiri di depan meja kayu pendek sepertinya bekas altar, banyak bekas gosong dari dupa yang jatuh. Sambil terus menumbuk, Maria mengangkat wajah dan menatapku lurus seolah aku pelanggan biasa.
“Kamu mau apa?” katanya. “Cleansing aura, jamu melupakan mantan, atau ramuan tidur cepat tanpa mimpi buruk?”
“Aku cuma lewat,” kataku sambil tertawa ringan.
Dia tertawa pendek, satu bahu naik. “Orang yang ‘cuma lewat’ biasanya butuh dua botol paling mahal dan satu pelukan.”
“Hahaha… Masuk akal. Tapi saat ini aku sedang berkelana mencari cerita. Lalu kulihat tokomu dari jauh. Aku merasakan sebuah panggilan,” kataku. “Dan aku belum ngopi. Siapa tahu kamu punya. Namaku Ervin. Ervin Ruhlelana.”
Maria menyipit sedikit, lalu matanya melebar penasaran. “Ah. Jadi kamu Ervin Ruhlelana. Seorang teman pernah menceritakan tentangmu padaku, dan saat itu aku berharap bisa menemuimu, setidaknya sekali dalam seumur hidupku. Dan mengejutkan! Tiba-tiba kamu masuk ke sini, ke ruang ini. Oh my godesses!” katanya sambil memegang mukanya, takjub. “Namaku Maria,” dia menambahkan.
Dia menyodorkan tangannya padaku. Aku refleks sedikit tegang. Lalu menyambut tangannya, menyalaminya, “Wow. Really! Nice to meet you then, Maria.”
“So really great to finally meet you, Ervin.” Dia masih memandangku seperti takjub. Aku merasakan wajahku panas. Aku membuang muka sambil pura-pura melihat relik-relik spiritual dalam sebuah showcase berbentuk dodecahedron yang tergantung di tengah ruangan.
“Ruhlelana, Sang Pendongeng Keliling, begitu temanku menyebutmu,” katanya dengan nada puas, seperti baru menemukan spesies burung langka di halaman belakang. “Penyihir hitam dari Sunda, katanya. Ayo duduk sini. Kita barter. Kamu kasih aku satu cerita, aku kasih kamu kopi dan sesuatu buat dibawa pulang.”
Aku duduk.
Jam di dinding menunjukkan 15:53. Hujan baru berhenti; air masih menetes dari atap alang-alang, titik-titik kecil jatuh di ember biru. Di luar masih ada suara motor, tapi ruang ini rasanya seperti tempat yang tidak sepenuhnya ada di peta. Aku tahu, karena tubuhku sedikit kesemutan. Kesemutan itu biasanya tanda dua garis bertemu.
“Kamu tahu aku penyihir hitam?” tanyaku.
“Aku Slavic witch,” katanya, lalu memainkan sendok kayu di cobek. “White witch. Tradisi ibuku bilang aku penyihir putih. Bahasa lokal kalian juga punya ‘penyihir putih’, kan? Tapi definisinya beda, ya?”
“Jauh,” kataku. “Di tanahku, penyihir putih itu penyihir yang pakai jubah putih dan baca mantra dalam bahasa Arab. Mereka datang setelah Islam masuk. Jadi sihirnya tetap sihir, tapi pakai pakaian agama supaya aman di mata publik. Penyihir hitam itu penyihir tua sebelum ada Islam. Baju kami hitam. Bukan karena jahat. Karena tua. Asal. Hitam itu warna tanah sebelum disinari. Ilmu tubuh-bumi sebelum dialihbahasakan jadi doa dengan materai halal.”
Maria mengangguk-angguk cepat, matanya berbinar seperti anak kecil yang baru tahu dinosaurus itu nyata. “Aku suka itu,” katanya. “Hitam sebagai sebelum. Bukan sebagai iblis. Itu bikin aku senang.”
“Kami nggak musuhan,” jelasku. “Putih dan hitam di Sunda bukan kayak film Hollywood. Putih bisa pakai teknik hitam, hitam bisa pakai teknik putih. Perbedaannya bukan pada tata cara, tapi pada tata niat. Kau bisa bikin orang tidur. Kalau kau bikin dia tidur supaya dia lupa untuk memukul istrinya, itu penyembuhan. Kalau kau bikin dia tidur supaya kau ambil barang-barangnya, itu perampokan. Ritualnya sama. Yang bikin namanya beda adalah tujuanmu.”
Maria tertawa pelan, puas. “Di tempatku,” katanya, “perempuan seperti aku dulu dipanggil ‘біла відьма’—penyihir putih. Tapi lucunya, orang-orang luar negeriku sekarang dengar istilah itu, terus mereka pikir itu artinya aku suci, vegan, penyayang unicorn, selalu bicara lembut, nggak suka kekerasan, anti-politik. Padahal, penyihir putih di desaku itu artinya: perempuan yang tahu cara bikin ramuan nggak mati kedinginan, tahu cara lahirkan bayi di gudang kentang, dan tahu cara bikin laki-laki pemabuk tidur sebelum dia sempat mukul siapa pun. Itu putih. Suci? Mana ada kata suci di salju dingin. Putih itu cuma warna salju, sayang. Salju itu nggak lembut. Salju bisa bunuh kamu.”
“Lucu ya,” kataku. “Kita sama-sama jatuh, jadi korban propaganda warna.”
Maria menunjukku dengan sendok kecil. “Exactly. Laki-laki suka naruh moralitas di warna. Hitam jahat, putih baik. Padahal, warna cuma pigmen dan cuaca. Kamu hitam karena kamu tua. Aku putih karena aku lahir di salju.”
“Itu barusan kalimat paling logis hari ini,” kataku.
Dia ngakak.
“Aku suka kamu,” katanya. “Kamu mau kopi Bali atau jamu hitam?”
“Kalau jamu hitamnya bisa bikin aku bahagia, aku mau. Tapi kopi juga cukup membahagiakan. ”
“Jamu hitam kalo begitu,” katanya. “You will like it.”
Dia menyiapkan jamu dengan gerakan yang tidak tergesa. Air panas dari teko enamel, bubuk jamu hitam dalam stoples kaca disendok lalu dituangkan ke gelas kaca bergores, diaduk sendok logam. Tidak ada latte art, tidak ada oat milk, tidak ada cardamom chai chakra whatever. Hanya jamu hitam kental dan meja kayu. Sambil mengaduk, dia melirikku lagi.
“Jadi,” katanya, “pendongeng keliling.”
“Pendongeng keliling,” kataku.
“Itu masih ada?” tanyanya.
“Enggak,” kataku. “Sudah punah.”
“Jadi kamu apa?” katanya.
“Aku fosil jalan kaki,” kataku.
Dia tertawa sampai bahunya naik-turun. “Oke, fosil. Jelasin. Kamu keliling kampung, kasih dongeng buat anak-anak biar mereka nggak main HP?”
“Bukan dongeng anak-anak,” kataku. “Aku nggak bawa kisah fabel atau cerita kerajaan. Aku bawa hidupku sendiri. Aku datang ke kampung, ke kampus, ke warung, kadang ke pos ronda, orang-orang kumpul, aku duduk, aku bilang: ini yang kualami kemarin. Aku ceritakan. Aku jujur. Aku buka semua pintu. Aku bilang, ‘Di Banyuwangi aku ketemu lelaki yang kepalanya bisa tahu gerhana tiga hari sebelum BMKG ngasih jadwal resmi’. Aku bilang, ‘Di Cirebon ada perempuan tua yang bisa ngobrol sama orang koma tanpa suara, dan itu menyelamatkan satu keluarga dari bunuh diri massal.’ Aku bilang, ‘Tadi malam aku mimpi orang lewat di sungai, tapi sungainya di atas kepala, dan paginya aku temukan bekas air asin di rambutku padahal kita jauh dari laut.’ Dan mereka bayar aku dengan rokok, nasi bungkus, kasur buat tidur. Kadang amplop. Itu pekerjaanku.”
Maria mendengarkan dengan serius. Matanya turun ke tanganku, lalu kembali ke wajahku. “Jadi kamu memelihara memori kolektif,” katanya perlahan. “Bukan dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk tubuh. Kamu bawa kisah hidup manusia sebagai barang dagangan bergerak.”
“Hmm… boleh juga kesimpulan itu, aku baru ngeh,” kataku sambil menerawang ke langit-langit toko.
Maria menghela napas. “Itu romantis,” katanya. “Romantis bukan kayak bunga mawar. Romantis seperti sistem ekologis yang hampir punah.”

Jam 16:07.
Maria menyodorkan kopiku, lalu bersandar di meja. “Sekarang giliranku,” katanya. “Aku kasih kamu ceritaku.”
“Aku siap.”
“Aku suka Putin,” katanya.
Aku berhenti separuh tegukan, bukan karena jamunya pahit sekali, tapi kaget aja.
Maria melihat reaksiku, lalu mengangkat dua tangan. “Tunggu,” katanya cepat. “Jangan lompat. Dengar dulu.”
“Aku dengar,” kataku sambil melanjutkan mereguk jamu pahit itu.
“Aku udah tinggal di sini sepuluh tahun,” katanya. “Orang-orang Bali baik padaku, orang-orang ekspat juga. Tapi setiap kali aku bilang aku mengagumi Putin, bule-bule—Amerika, Australia, Inggris— langsung marah. Mereka bilang aku bego politik. Padahal bukan itu. Aku jelasin capek. Jadi aku berhenti jelasin. Sekarang aku jelasin lagi, tapi cuma karena kamu tampak bisa memegang cerita tanpa menusuknya pakai moral instan.”
“Jelaskan,” kataku.
“Aku lahir di tempat dingin,” katanya pelan. “Kamu tahu dingin? Aku maksud bukan AC. Aku maksud dingin minus dua puluh derajat, dingin yang bisa bunuh bayi selama satu malam kalau atap rusak. Di tempat dingin, laki-laki yang bisa berdiri di depan pintu dan bilang ‘tidak ada yang masuk rumah ini untuk sakiti keluarga ini’ adalah konsep keselamatan. Aku tumbuh dengan imaji itu. Paham? Itu bukan fetish kuasa. Itu survival.”
“Jadi kau kagum pada ide proteksi,” kataku.
“Ya,” katanya. “Aku kagum pada imaji pagar. Aku bukan cinta laki-lakinya. Aku cinta kemungkinan bahwa ada pagar yang bilang ke dunia: ‘Perempuan ini tidak kalian ubek-ubek.’ Karena kalau ada pagar, aku bisa kerja. Aku bisa nolong perempuan lain. Aku bisa buka tempat ini tanpa takut polisi masuk dan bilang ‘izin mana, visa mana, pajak mana, mana suamimu’. Kamu ngerti?”
“Ngerti,” kataku. “Kau meminjam bayang laki-laki kuat sebagai perisai hukum sementara, biar kau bisa menciptakan ruang perempuan yang tidak bisa diacak-acak.”
Maria menunjukku. “Iya. Kamu pintar atau kamu pernah jadi perempuan?”
“Aku dengerin perempuan,” kataku. “Sama saja.”
Maria menatapku lama. Senyumnya turun jadi sesuatu yang lebih tenang. “Terima kasih,” katanya pelan.
“Sama-sama.”
Lalu dia balik nanya, nadanya berubah nakal lagi. “Kamu sendiri gimana? Di Sunda, penyihir hitam laki-laki dapat posisi apa?”
Aku tersenyum miring. “Tergantung siapa yang cerita,” kataku. “Kalau kau tanya kiai, jawabannya: aku sesat tapi lucu. Kalau kau tanya ibu-ibu pasar, jawabannya: aku orang yang bikin anak mereka sembuh panas dalam semalam jadi mereka akan masakin aku sayur asem seumur hidup. Kalau kau tanya polisi, jawabannya: aku ilusi. Tidak resmi ada.”
“Kalau aku tanya kamu?” bisik Maria.
Aku menatap gelas jamu. “Aku juru tulis yang tidak resmi diakui negara,” kataku. “Aku catat semua hal yang negara tidak mau catat: rasa takut perempuan, rasa malu laki-laki, perjanjian rahasia antar kampung, dan garis-garis naga di bawah kaki kita.”
Maria nyaris melompat. “Ha!” katanya sambil menepuk meja. “Aku tahu! Aku rasa itu tadi. Aku rasa sejak kamu masuk. Udara langsung getar. Kamu ngerasain juga kan?”
Aku diam sebentar. Tengkukku tadi memang hangat sejak aku lewati ambang pintu. Bukan hangat erotis. Hangat geologi. Seperti berdiri di atas retakan bumi yang ada magmanya.
“Aku rasa,” kataku pelan, “kita lagi di salah satu titik temu.”
Maria maju sedikit, mata biru abu-abunya membesar. “Yes,” bisiknya. “Yes yes yes. Oke dengar. Aku udah simpan teori ini lama banget dan semua orang bilang aku terlalu banyak LSD, padahal aku nggak suka LSD karena bikin aku pusing mual. Jadi dengar, dan jangan ketawa dulu.”
“Aku nggak ketawa,” kataku.
“Dunia punya dua naga,” kata Maria, cepat, antusias seperti anak lima tahun menjelaskan meteor. “Bukan naga Eropa. Aku nggak bicara yang bersayap besar, bersisik hijau metalik, duduk di puncak kastil sambil jaga putri dan emas. Bukan. Aku bicara naga panjang. Naga Cina. Tubuh seperti ular panjang yang lentur, tapi ada tiga pasang kaki pendek dengan cakar bagus buat mencengkeram batu dan akar. Mereka tidak punya sayap, tapi mereka bisa terbang. Mereka juga bisa berenang, menyelam, bernapas di air. Mereka bisa melilit bumi. Mereka adalah arteri planet.”
Aku meneguk kopi perlahan. “Yup, aku paham. Lanjut.”
“Naga pertama melilit bumi secara horizontal seperti gelombang sinus,” katanya sambil menggambar di udara pakai sendok kayu. “Bayangkan garis ekuator sebagai garis tengah. Naga ini bergerak sedikit di utara, lalu ke selatan, naik lagi, turun lagi, jadi garisnya bukan lurus, tapi bergelombang manis. Naga kedua melilit bumi juga secara horizontal tapi dalam pola kosinus—masih mengacu ke khatulistiwa, tapi puncak dan lembahnya beda. Dua naga ini saling silang di dua titik yang selalu sama sepanjang sejarah manusia: satu di Bali, satu di Peru. Itu titik di mana getaran mereka bertemu dan sinkron.”
Aku mengangguk. “Itu kenapa begitu aku masuk sini aku dengar dengung rendah kayak gardu listrik.”
“Yup,” katanya cepat. “Itu frekuensi. Itu panggilan. Karena kamu naga satunya, dan aku naga satunya lagi.”
“Kita naga?” Tanyaku, sekalian menguji rasanya kalimat itu di mulutku sendiri.
“Ya,” katanya enteng, seolah bicara, “Ya, aku Aquarius.”
Aku tidak langsung jawab. Tapi tubuhku menjawab. Kulit di sepanjang lengan kiriku tiba-tiba seperti ingat sesuatu yang bukan kulit: tekstur sisik halus, bukan sisik reptil kering, tapi sisik basah, licin, ringan, seolah tubuh panjangku bisa meliuk di laut dan di udara tanpa ganti mode. Aku juga merasakan sesuatu yang seperti kaki—tiga pasang, bukan dua—mencengkeram bebatuan karang tua di laut dangkal dekat garis pantai yang tidak ada di peta modern. Perasaanku seperti pulang ke sesuatu yang dulu sangat biasa tapi sekarang terasa mitos. Kurasa efek jamu hitamnya mulai bekerja.
Maria memejam sebentar. “Aku sekarang lagi lihat kita dari atas,” katanya lirih. “Kita berdua bukan manusia. Kita dua garis cahaya bergerak, memeluk dunia. Kita saling kejar di sepanjang khatulistiwa, kadang kamu sedikit di utara, aku sedikit di selatan. Kadang aku naik, kamu turun. Dan cuma di Bali dan Peru kita benar-benar tumpang tindih, tubuh kita bersilang, seperti dua ular tua saling peluk. Ketika itu terjadi, bumi… klik. Kayak jantung di-reset. Kayak bumi ngambil napas panjang.”
Aku mengangkat alis. “Dan itu terjadi sekarang?”
Maria membuka mata. “Itu terjadi setiap kali kita ngobrol begini tanpa rencana,” katanya. “Jadi ya. Dengan kata lain: sekarang bumi lagi take a deep breath.”
“Selama kita di ruangan ini?”
“Selama kita jujur,” katanya.
Aku tersenyum kecil. “Jadi kalau kita mulai basa-basi small talk cuaca, bumi berhenti napas?”
“Ya,” katanya. “Makanya jangan tanya aku ‘how’s Bali treating you so far’, please.”
Kami tertawa bersamaan. Rasanya ringan dan tua sekaligus.

Jam 16:27.
Waktu jadi cair. Hujan sudah benar-benar berhenti; ada cahaya lembut masuk dari celah dinding bambu, memantul di botol-botol kaca kecil yang berisi cairan hijau, kuning, cokelat pekat. Ada lalat buah mengitari buah jeruk purut di mangkuk. Dari jalan terdengar satu “Om Swastiastu” dari turis mabuk spiritual. Dunia berjalan normal. Tapi di dalam ruangan ini garis bumi sedang ditulis ulang, dan tidak ada sirine negara untuk itu. Hanya kami.
“Aku mau tanya,” kataku. “Di desamu dulu… perempuan penyihir seperti kamu. Dianggap apa?”
Maria menghela napas, lalu bicara pelan. “Dianggap perlu,” katanya. “Dan karena dianggap perlu, kami juga dianggap berbahaya. Lucu kan? Kamu cuma dianggap berbahaya kalau kamu benar-benar diperlukan.”
“Ironi.”
“Kami yang tahu cara menggugurkan kandungan tanpa bunuh ibu,” katanya. “Kami yang tahu cara berhentiin pendarahan rahim setelah dipukul. Kami yang tahu jamu buat trauma tidur. Kami yang tahu cara bikin anak demam tiga hari turun tanpa rumah sakit. Jadi laki-laki di desa kami datang ke kami tengah malam, mengetuk jendela, suaranya bergetar, ‘tolong istri saya’. Mereka butuh kami. Tapi paginya, di depan umum, mereka bilang kami bahaya. Karena perempuan yang tidak takut mati—perempuan yang bisa pilih mau hamil atau tidak, mau tidur nyenyak atau tidak—itu ancaman buat sistem. Sistem suka perempuan yang capek, lapar, mengantuk, takut.”
Aku menatapnya. “Jadi kamu pelan-pelan mencuri hak atas tubuh kembali.”
“Ya,” katanya. “Itu selalu inti sihir perempuan. Ini bukan soal terbang di atas sapu. Itu propaganda barat. Sihir perempuan inti dasarnya cuma satu kalimat: tubuhku wilayah berdaulat. Titik. Dan negara benci kalimat itu. Gereja benci kalimat itu. Bahkan beberapa feminis korporat benci kalimat itu, karena kalau tubuhku berdaulat, aku tidak bisa dijual sebagai brand empowerment pink 20% off.”
Aku hampir tersedak jamu karena ketawa.
Maria melotot manis. “Jangan pura-pura kamu nggak paham,” katanya. “Kalian di Jawa dan Sunda sama, kan? Laki-laki boleh mistis sepanjang mistisnya pakai bahasa agama, pakai peci, pakai nada rendah khidmat. Tapi kalau perempuan mistis, langsung dibilang ‘sundel’, ‘pelesir dengan jin’, ‘bahaya untuk moral desa’. Benar atau benar?”
“Benar,” kataku pelan. “Kami tumbuh besar diperingatkan soal perempuan semacam kamu bahkan sebelum kami tahu apa itu clitoris. Tapi anehnya, ketika kampung beneran butuh pertolongan, mereka cari siapa? Perempuan seperti kamu.”
Maria menunjukku bangga. “Exactly. Kamu ngerti. Makanya aku pilih suka kamu.”
“Kamu suka aku atau kamu suka bahwa aku ngerti?”
“Bedanya apa?” Katanya, tersenyum bengal.
Aku tertawa.

Jam 16:41.
Aku merasa tenang, kurasa masih efek jamu, tapi tak kutanyakan pada Maria, kunikmati saja. Lalu ada sesuatu yang meluruh dari punggungku, seperti beban yang kupikul dari satu desa ke desa lain—cerita perempuan yang dipukul, cerita laki-laki yang tidak boleh nangis, cerita kampung yang takut aparat, cerita mahasiswa yang takut dilabeli gila—semuanya biasanya nempel di tulangku. Sekarang sebagian turun. Bukan hilang, cuma… terbagi.
“Mari kita buat kontrak,” kataku tiba-tiba.
Maria mengangkat dagu. “Kontrak gimana?”
“Kontrak naga,” kataku. “Kalau kita memang dua naga yang melilit bumi, kita harus bikin perjanjian yang tidak bergantung pada negara, agama, atau algoritma. Sesuatu yang cuma punya dua pihak: kamu dan aku. Horizontal. Tanpa atasan.”
Maria mencondongkan tubuh. “Aku dengar.”
“Gini,” kataku. “Kamu jadi titik aman buat perempuan di radiusmu. Kamu terus lakukan itu. Kamu bikin jamu untuk luka-luka yang polisi nggak tulis di laporan. Kamu kasih tarot sebagai bahasa alternatif buat orang yang nggak bisa bicara langsung soal rasa takutnya. Kamu pakai kata-kata yang negara belum tahu cara mengawasi. Kamu terus jadi penyihir putih dalam definisi asalmu.”
“Oke,” katanya, matanya tidak lepas dariku. “Dan kamu?”
“Aku jalan,” kataku. “Aku keliling seperti biasa. Tapi selain bawa cerita, aku mulai bawa garismu. Setiap kali aku mampir kampung, kampus, pos ronda, aku bilang ke perempuan di sana: di Bali ada toko kecil, ada perempuan pirang matanya biru-abu, kulitnya madu terbakar, namanya Maria, dan dia bilang tubuhmu boleh berdaulat. Aku tanam kalimat itu di kepala mereka. Supaya mereka tahu pagar itu nyata. Bukan mitos.”
Maria menatapku lama, bibirnya sedikit terbuka. “Jadi kamu broadcast sinyalku.”
“Ya. Kamu jadi stasiun induk. Aku jadi repeater keliling.”
Maria menutup mata sebentar lalu membukanya lagi. “Tuhan cinta jaringan mesh,” katanya lirih.
“Siapa Tuhanmu, Masha?” godaku.
Maria mengangkat bahu. “Tergantung jam. Sekarang? Sekarang Tuhanku perempuan tua tanpa nama yang duduk di bawah meja ini, mengelus kepala kita, bilang ‘lanjutkan, cucu, lanjutkan’.”
Aku mengangguk. “Itu juga Tuhanku sekarang.”
Maria meraih sesuatu dari rak belakang: sebuah liontin kecil dari batu hitam, dibungkus kawat tembaga, digantung di tali kulit. Ia meletakkannya di telapak tanganku. Batu itu berat kecil, hangat seperti sudah lama menyimpan tangan.
“Ini bukan jimat murah,” katanya serius. “Ini serpihan bekas fondasi rumah ibuku yang terbakar waktu aku dua belas. Rumah itu kebakaran bukan karena lilin jatuh. Rumah itu dibakar orang-orang kota setelah ibu menolak bantu seorang pejabat-istri-nya supaya hamil padahal tubuh perempuan itu sudah hampir mati. Ibuku bilang, ‘kalau aku paksa rahimmu kerja, kamu mati, dan aku nggak mau jadi alat pembunuhan pelan buat laki-laki yang mau pewaris’. Esok paginya rumah kami hangus. Ibuku ketawa lihat api. Dia bilang, ‘Lihat, Masha, bahkan mereka harus panggil empat laki-laki buat jatuhkan satu perempuan kecil dan anak perempuannya. Itu statistik yang bagus.’”
Maria menatapku. “Aku masih hidup karena potongan rumah itu. Simpan.”
Aku meraih napas. “Kalau aku simpan, kamu pakai apa?”
Dia mengangkat kedua tangannya, lalu menunjuk ke dadanya sendiri. “Aku punya rumah baru,” katanya. “Rumahnya: tubuhku. Ini yang aku bilang tadi. Tubuhku wilayah berdaulat. Kamu bawa serpih rumah lamaku, jadi kamu ingat: ada perempuan yang pernah memilih hidupnya sendiri sementara negara ingin memilih untuknya.”
Aku ingin menjawab dengan sesuatu yang cerdas, tapi tenggorokanku mengetat. Jadi yang keluar cuma, “Terima kasih, Masha.”
Maria mengangguk kecil. “Sekarang kontrakku,” katanya. “Aku akan bilang ke semua perempuan yang datang kemari, semua teman, semua pendatang baru, semua ibu-ibu banjar yang bisik-bisik sambil bawa sayur pagi… aku akan bilang: ada lelaki Sunda berpakaian hitam yang keliling dari kampung ke kampung, bawa cerita bukan buat pamer kekuatan tapi buat nyambungin luka orang ke luka orang lain supaya luka mereka tidak merasa sendirian. Dan aku akan bilang ke mereka: lelaki ini bukan predator. Dia tidak mau tidur sama kamu sebagai pembayaran cerita. Dia cuma mau kamu masih hidup minggu depan. Namanya Ruhlelana. Kalau kamu dengar cerita dia, percaya. Kalau kamu capek, titipkan sedikit capekmu padanya. Dia tahu cara bawa beban tanpa drama heroik laki-laki.”
Aku spontan ketawa kecil. “Aku merasa dipromosikan,” kataku.
“Itu iklan media sosial,” katanya.
Kami saling menatap. Ruangan terasa lebih sunyi. Tapi itu bukan sunyi kosong; itu sunyi seperti setelah gempa kecil: semuanya masih bergerak sedikit, tapi pelan.

Jam 16:58.
Maria berkata pelan, “Kamu sadar kan, ini baru empat puluh satu menit.”
“Aku sadar,” kataku.
“Kamu sadar kan, setelah kamu keluar nanti, dunia akan terlihat sama persis bagi orang lain, padahal tidak sama lagi.”
“Aku sadar,” kataku. “Itu kerja kita kan? Bikin perubahan yang tidak bisa dibuat konferensi internasional, tidak bisa dibeli dengan donor asing, tapi cukup kuat buat bikin satu anak kecil ngerasa aman tidur malam ini. Itu skala kita. Skala naga.”
Maria tersenyum. “Kamu romantis juga ternyata, Ervin.”
“Aku pendongeng, Masha,” kataku. “Kalau pendongeng nggak romantis, kami berubah jadi humas.”
Maria ngakak keras, sampai hampir jatuh dari kursinya. Gelang di pergelangan kakinya berbunyi kecil—bunyi logam bertemu logam, seperti dua koin tua saling sapa.

Jam 17:02.
Aku berdiri perlahan. Kaki kiriku sedikit kesemutan, seperti ekor panjang yang sudah lama kulupakan ingin meregang. Maria juga berdiri. Kami berdiri dekat, tapi bukan dekat erotis. Dekat koordinat. Seperti dua garis peta yang akhirnya ketemu setelah memutari bola bumi.
Maria berkata pelan, “Kalau nanti kamu pergi ke Peru—”
“Aku belum punya tiket Peru,” potongku.
“Kamu akan sampai di Peru,” katanya yakin. “Entah besok, entah sepuluh tahun lagi, entah lewat mimpi. Kalau kamu sampai di Peru dan kamu merasa udara tiba-tiba bergetar seperti gardu listrik lagi, dan kamu merasa tubuhmu panjang, licin, punya tiga pasang kaki kecil, ingat aku. Dan bilang ke udara kalimat ini: ‘Tubuhku wilayah berdaulat.’ Aku akan dengar dari sini. Atau mungkin aku juga sedang ada di sana”
Aku mengangguk. “Kalau kamu tiba-tiba ngerasa sendirian di sini,” balasku, “kalau turis-turis yoga mulai cerewet soal vibrasi, kalau aparat nanya izin usaha terlalu sering, kalau suatu malam kamu takut, bilang ke udara: ‘Aku fosil jalan kaki.’ Aku akan dengar dari mana pun aku lagi bercerita.”
Maria menghela napas lega. “Deal,” katanya.
Kami berpelukan, berciuman, lalu saling menatap sebentar, seperti dua naga tua melingkarkan tubuh di sekitar khatulistiwa, saling sentuh sebentar untuk memastikan planet masih punya detak.

Jam 17:10.
Aku melangkah ke pintu bambu, melewati deretan kristal, tongkat sihir, botol ramuan tidur tanpa mimpi, dan kartu tarot yang menyimpan wajah-wajah dewa tua yang tidak pernah masuk kurikulum nasional. Sebelum aku keluar, Maria memanggil.
“Ervin, sayang.”
Aku menoleh, “Yes, my dear Masha?”
Dia tersenyum kecil. Cerianya kembali, hangatnya kembali, manis seperti pertama kali aku masuk. “Jangan lupa satu hal,” katanya.
“Apa?”
“Kamu bukan hitam,” katanya. “Kamu cuma lebih tua dari lampu.”
Aku tertawa. “Dan kamu bukan putih,” kataku. “Kamu cuma lahir di salju.”
Maria mengedip nakal. “See you di Peru, nagaku.”
Aku keluar ke jalan kecil Ubud yang basah, ke udara sore yang masih hangat, ke suara motor, ke dunia yang tampaknya sama tapi tidak kembali sama. Di tulang belakangku masih ada rasa sisik naga yang perlahan kembali diam. Dua gelombang—sinus dan kosinus—sudah berpisah lagi, kembali ke orbit masing-masing mengelilingi bumi secara horizontal dengan khatulistiwa sebagai panduan garis tengahnya.
Dan bumi—kalau kau taruh jarimu di tanah saat itu, kau mungkin akan merasakannya—bernapas sedikit lebih lega.