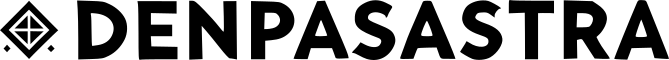Sudah 15 tahun saya membawa kartu tarot ke mana-mana, awalnya hanya untuk media merayu perempuan, bagai melihat garis tangan, baca tarot buat kecengan selalu berhasil membuat mereka tercengang dan menjadi rentan untuk dipeluk. Namun sejak saya memutuskan untuk menjadi pembaca tarot profesional, saya membuat peraturan yang mirip seperti etika kedokteran dan psikologi, tidak boleh tidur dengan klien. Peraturan ini saya buat untuk menjaga diri sendiri agar tidak memanipulasi interpretasi seperti yang saya lakukan saat masih muda dan bodoh.
Saya memulai karir profesional ini tahun 2023 di Tangerang atas desakan teman-teman di sana. Mereka bilang bahwa saya bisa mendapat uang dari membaca tarot seperti ini. Maklum, teman-teman saya itu mayoritas Tionghoa—yang mengaku sendiri bahwa di mata mereka, apa saja bisa jadi cuan. Saya setuju dengan usul itu dan mereka mengapresiasinya dengan menghadirkan teman-teman mereka ke rumah saya untuk menjadi klien. Ternyata asik juga punya uang yang rasanya jatuh dari langit, tak perlu mengeluarkan modal material, cukup mengandalkan kecerdasan dan intuisi. Saya merasa bodoh, kenapa tidak dari dulu minta bayaran buat tarot? Tapi saya sudah tahu jawabannya, karena waktu muda saya memang bodoh, idealis, alergi uang, dan pertemanan jauh lebih berharga dari uang—meskipun di kemudian hari saya belajar bahwa kadang uang bisa membeli pertemanan, saya benci realitas itu!
Sepeninggal dari Tangerang, saya melanjutkan karir profesional sebagai tarot reader di pusatnya langsung, pusat pergerakan spiritual dunia. Banyak orang yang bermasalah secara domestik menjadikan Ubud sebagai tempat pelarian yang bertopeng healing dengan komoditas lengkap seperti retreat dan yoga center, pusat-pusat meditasi, kantong-kantong komunitas spiritual dari berbagai ajaran berbeda, dan tentu saja—tarot reading session, yang tersebar begitu banyak tanpa poster di seantero Ubud. Boleh dibilang orang yang ke Ubud hampir pasti minimal punya satu set kartu tarot.
Keadaan ini memberikan saya tujuan baru dalam hidup, yaitu membantu sebanyak mungkin orang yang membutuhkan jasa saya dan melihat uang tak lebih dari sekadar karma baik penukar energi. Dan sejauh ini, saya rasanya sudah membantu lebih dari 1000 orang menemukan solusi atas masalah dalam hidupnya—beberapa dari klien saya kadang datang hanya untuk mencari afirmasi atas hal yang akan atau sedang dia lakukan. Namun satu hal yang pasti, meja tarot saya boros tisyu. Klien saya yang kebanyakan perempuan, kadang mereka datang hanya untuk numpang nangis, melepas air mata yang sukar keluar dalam realitas di luar yang senang menggigit—karena itu saya mendesain ruang tarotku jauh dari kesan realitas, agar klien saya sejenak melupakan realitas mereka. Dinding-dinding saya pasangi lukisan surealis, harum dupa tak pernah padam, batu-batu kristal, dan musik dari playlist Psychedelic Chillout atau Psychedelic Chill Mix.
Di antara sekian banyak orang dari berbagai belahan dunia yang masuk ruang tarot saya selama lebih dari setahun terakhir ini di Bali, selalu ada orang-orang yang minta dibacakan masa depan. Sejak saat itu, saya selalu memberikan disclaimer pada calon klien saya bahwa saya tidak membaca masa depan, saya hanya membantu memberikan gambaran besar masalah yang sedang dihadapi, dan bersama-sama mencari solusi berdasarkan petunjuk kartu.
Pada beberapa klien yang bertanya secara serius kenapa akurasi kartu tarot begitu tinggi, saya menjelaskan pada mereka bahwa kartu tarot lebih matematis ketimbang mistis. Jika saya diberikan kesempatan menulis essay tentang pernyataan itu maka yang kira-kira akan saya tulis adalah essay di bawah ini:
Aku selalu suka berpura-pura: di atas meja, orang kira aku sedang bersekutu dengan kabut dan intuisi; padahal yang kukerjakan jauh lebih membumi—lebih kering dari angka-angka di papan tulis kampus. Tarot itu, sayangku, bukan mesin kabut. Ia adalah mesin kombinasional. Sebuah kalkulator simbol yang menyamar sebagai cermin. Bila mistis adalah kabar angin, maka kartu adalah struktur: 78 kartu, 22 di antaranya arkanum besar yang keras kepala seperti huruf kapital sejarah, 56 lainnya arkanum kecil yang lincah seperti huruf kecil di pesan singkat. Kita bukan mengusir rasionalitas dari meja; kita mengundang probabilitas duduk ikut minum.
Hitunglah sebentar, jangan takut. Satu kartu pertama yang kau buka punya peluang kira-kira 28,2% menjadi arkanum besar. Tarik tiga kartu, dan peluang setidaknya satu arkanum besar mampir melonjak jadi kurang lebih 63,6%. Tarik sepuluh kartu ala “Celtic Cross”—yang sering disangka paling teatrikal—dan peluangmu menyentuh arkanum besar nyaris pasti, sekitar 97%. Ini bukan mantra, ini distribusi. Ketika seseorang terperangah melihat tiga arkanum besar muncul berurutan, aku tersenyum kecil: harapan manusia selalu salah mengira kelangkaan. Padahal peluang “dua atau lebih arkanum besar dalam tiga kartu” masih sekitar 19%. “Keajaiban” seringkali cuma kebutaan kita pada proporsi.
Sekarang mari kita mengintip hutan kemungkinan. Satu pembacaan sepuluh kartu, bila urutan diperhitungkan, punya ruang keadaan sekitar 4,566×10¹⁸. Kau tambahkan orientasi terbalik (reversed) sebagai variabel biner, ruangnya meledak menjadi kurang lebih 4,676×10²¹. Itu setara dengan kurang lebih 72 bit informasi—cukup untuk menyandikan tragedi keluarga beserta nomor telepon mantan. Kau menamai ini takdir; matematika menyebutnya entropi. Dan entropi, dalam pembacaan, bukan musuh—dia bensin bagi makna.
Lalu datang pertanyaan yang lebih menggoda: kalau segalanya angka, di mana “pesan” itu tinggal? Di sinilah tarian dimulai. Simbol-simbol di tarot bukan kamus yang dingin; mereka lebih mirip basis data dengan skema longgar: setiap kartu memuat klaster makna yang saling beririsan. Sang Ratu Piala membisikkan empati, keintiman, bias kelembutan yang bisa berubah jadi kabut; Delapan Pedang menata rasa terjebak, prasangka pada diri sendiri; Menara adalah kegagalan struktural yang menyamarkan karunia. Pembaca tarot yang baik bukan peramal—ia perancang kueri. Ia memilih subset relevan dari semesta makna berdasarkan pertanyaan yang diajukan penanya, lalu menjalankan “pembaruan keyakinan” sederhana: sebelum kartu dibuka, kita punya prasangka tentang cerita; setelah kartu jatuh, kita memperbarui peluang cerita-cerita yang mungkin. Orang laboratorium menyebutnya teorema peluang bersyarat; nenekku menyebutnya, “Coba pikir lagi setelah melihat ini.”
Kau lihat, prosesnya sangat mirip dengan cara otak manusia bekerja mencari pola. Kita membawa prior—riwayat luka, harapan, gosip keluarga, harga cabai di pasar—lalu kartu memasok evidence yang kaya namun ambigu. Ambiguitas di sini bukan kelemahan; justru kekuatan. Ia memberi kebebasan bagi kognisi untuk menyusun hipotesis dan menguji resonansinya di tubuh: apakah kalimat ini membuat dada sesak atau justru melonggar? Apakah ilustrasi Hanged Man, yang kepala terbalik itu, membuatmu ingat proyek yang sengaja kau parkir karena kamu tahu memaksa maju akan membuatnya rusak? Ketika otot-otot wajahmu bergerak, ketika napasmu berubah, itulah saat posterior keyakinanmu bergeser. Itu matematika—bukan debu peri.
Di titik ini, kabar buruknya untuk para pembenci angka: bahkan keacakan yang kaudoakan dalam shuffle pun punya teori. Riffle shuffle pada 52 kartu dianggap “cukup acak” sekitar tujuh kali pengocokan; untuk 78 kartu, kau butuh sedikit lebih banyak. Tentu, tangan manusia jarang sefatal mesin; selalu ada bias kecil: kecenderungan memecah tumpukan pada posisi tertentu, tekanan ibu jari yang tak konsisten. Bias-bias inilah yang membuat beberapa kartu terasa “sering keluar” untuk klien tertentu. Bukan karena semesta doyan mengulang drama, tapi karena manusia mengulang pola motorik plus pola hidup. Statistik tak merusak romantika; ia justru membongkar rahasia bagaimana kita diam-diam bekerja sama dengan kebetulan.
Struktur internal tarot juga matematis: empat gugus (Tongkat, Piala, Pedang, Koin) adalah empat vektor gaya hidup—energi, emosi, pikiran, material—yang saling menyeimbangkan seperti persamaan empat variabel. Empat belas tingkat di tiap gugus memetakan gradien intensitas dari Ace (definisi murni) hingga King (institusi). Arkanum besar berperan sebagai operator—mereka mengubah “basis” pembacaan. Ketika Keadilan turun di atas lima kartu minor yang sibuk, ia seperti koefisien yang memaksa sistem mencari solusi yang lebih lurus, atau setidaknya mengakui biasnya. Ketika Roda Fortuna muncul, ia seperti operator rotasi—soal yang sama, sudut pandang bergeser 90 derajat. Ini bukan dukun; ini aljabar yang kebetulan berwajah indah.
“Kalau begitu, mana tempat mistisnya?” tanyamu sambil menggulung rokok, separuh takut kehilangan bintang-bintang. Tenang. Yang selama ini kita panggil mistis sering kali adalah rasa takjub ketika struktur besar menyentuh pengalaman kecil. Sehelai kartu yang jatuh, dari triliunan konfigurasi, kebetulan memetakan dilemamu hari ini dengan presisi yang membuatmu terdiam. Keterdiaman itu bukan karena roh berkaki ayam melompat dari card stock; ia terjadi karena otakmu menemukan kompresi data yang menakjubkan: 10 gambar berhasil merangkum 3 tahun hidupmu menjadi satu kalimat yang akhirnya bisa kamu ucapkan. Keterucapan itulah mukjizatnya. Dan setiap mukjizat, bila ditelusuri, punya jejak angka.
Apakah ini berarti tarot “terbukti ilmiah”? Tidak. Tarot bukan alat ukur seperti termometer; ia lebih mirip mesin penanya. Ia meminta klarifikasi pada realitasmu. Tetapi menolak tarot sebagai “sekadar mistik” juga malas: ini adalah sistem terstruktur yang bekerja karena tiga hal yang sangat matematis—(1) ruang kemungkinan yang besar, (2) basis simbol yang saling bertaut, (3) mekanisme pembaruan keyakinan yang responsif pada bukti. Sisanya adalah seni: bagaimana menyusun output menjadi kalimat yang tidak memalukan di hadapan rasa sakit orang lain.
Dan karena kita hidup di Nusantara, kita tahu betul: angka dan mantra tidak pernah benar-benar berpisah. Pedagang di Pasar Baru memakai kalkulasi laba rugi sekaligus baca gerak mata pelanggan; nelayan di Puger menghafal pasang-surut laut sambil memeriksa tanda-tanda di langit. Tarot berdiri di simpang itu: satu kaki di statistik, kaki lain di sasmita. Kita tidak perlu mengusir satu demi yang lain. Yang penting adalah etika: jangan menjadikan kartu sebagai palu vonis, apalagi memeras ketakutan; jadikan ia papan tulis di mana seseorang bisa menggambar ulang rencana hidupnya—dengan penghapus tersedia.
Kukira ini alasan mengapa aku tetap setia pada kartu: bukan karena ia berbisik rahasia dari balik tirai, melainkan karena ia memaksa kita mengakui disiplin. Disiplin untuk menafsir berdasarkan bukti yang jatuh, bukan berdasarkan nafsu; disiplin untuk memeriksa bias, menguji ulang asumsi, menerima bahwa kadang-kadang Menara memang harus runtuh agar fondasi bisa diukur ulang. Matematis bukan berarti dingin. Ia justru kasih sayang yang rapi: tidak menjanjikan surga instan, tetapi menawarkan koordinat agar kau bisa berjalan sendiri, sampai jauh, sampai lega.
Dan seperti yang selalu kukatakan pada semua klienku di akhir sesi:
“Semoga bisa membantu!” maka dalam akhir tulisan aku juga akan berkata, “Semoga tulisan ini bisa membantu—membantumu memahami probabilitas nasib dan ketepatan takdir, sebab takdir adalah pertautan antar nasib, berkelindan dalam suatu gugus kompleks kombinasi dari anasir-anasir harapan dan segala entitas kekecewaan dalam berbagai level kesulitan.”
***
Jika kamu membutuhkan jasaku, aku akan sangat senang membantumu, hubungi saja lewat
WA: +62-878-2022-9777
Address: Iweng Art House, Jl. Pantai Kedungu No.3495, Belalang, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali 82121